Oleh: Triwibs Kanyut
“Temani aku meraung, kawan …” kata Heru S. Sudjarwo.
Habent sua fata libelli (setiap buku punya takdirnya sendiri-sendiri). Pada awalnya adalah “raungan” di suatu status facebook – sebagaimana galibnya raungan, ia mengandung semacam campuran rasa sakit, perih, amarah dan kekecewaan. Dan raungan biasanya terdengar begitu keras, memekakkan, meledak tetapi juga terasa mengiris, pilu.
Raungan Mas Heru, yang terkadang lebih akrab kami panggil Chuck Brewok, seolah mewakili raungan 400 lebih tokoh wayang yang terlantar di tengah suara gemuruh “Juggernaut” kebudayaan popular yang seperti hendak membabat habis kearifan kebudayaan, mengabaikan local genius, menjadikan dunia begitu dangkal, banal, dan tak sempat untuk barang sejenak merenungi kehidupan dari perspektif yang lebih dalam dan manusiawi.
Ketika kudengar raungan itu, seolah-olah aku mendengar raungan kebudayaan leluhur yang pelan tapi pasti secara tak sengaja terlupakan, atau sengaja disisihkan oleh laju modernitas yang bergerak tak tentu arah. Dan ketika kudengar raungan itu, mendadak membayang masa kecilku di suatu kota kecil, saat begitu terpesona oleh lakon-lakon wayang, yang saat itu belum kupahami sepenuhnya apa-apa makna tersirat yang ada di dalamnya. Raungan itu menerbitkan kembali kerinduan kepada kisah-kisah wayang, meriapkan kembali keinginan untuk membaca tokoh-tokohnya yang konon jumlahnya lebih dari 1000 karakter. Saat kemudian aku mengontak penulisnya dan mendapatkan sedikit gambaran tentang naskah ini, aku langsung sadar, tanpa bermaksud melebih-lebihkan pujian, betapa berharganya naskah ini bagi generasi muda saat ini. Kini salah satu bagian dari warisan itu akan segera hadir dengan kemasan baru yang lebih indah dan modern tanpa meninggalkan unsur kearifan dan keindahan seninya. Buku ini hadir demi kepentingan generasi muda kita yang barangkali lebih mengenal tokoh-tokoh superhero asing yang dangkal karakterisasinya dan tidak membuat kita merenung lebih mendalam. Buku ini seperti hendak menyadarkan kita bahwa jati diri kita sebagai manusia pada umumnya, dan kultur Nusantara pada khususnya, didasarkan pada perenungan tentang kearifan hidup, sebab hanya dengan perenungan kearifan itulah sesungguhnya barulah hidup layak untuk dijalani: bukankah Socrates pernah mengatakan “Hidup yang tak direnungi tak layak untuk dijalani?”
Barangkali, sepanjang aku menjadi editor buku sejak tahun 2000, inilah buku pertama yang membuatku -- sebagai editor yang sesungguhnya punya hak untuk campur tangan -- secara sadar beringsut ke belakang, menatap prosesnya dari dekat namun sama sekali tak ingin dan tak berani “bludusan” dalam proses kelahirannya dengan membawa keangkuhan formalitas editorial. Karenanya izinkan aku kisahkan alasan mengapa aku tak kuasa ikut serta dalam penyusunannya.
Sebuah buku yang baik adalah buku yang lahir dari cinta, lahir dari hati – dan buku semacam ini adalah langka:: dan ini adalah salah satu buku langka semacam itu. Ia ditulis dengan sepenuh hati yang dipenuhi cinta kepada tradisi leluhur. Tanpa ada cinta, barangkali kita tak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya perjuangan untuk mewujudkannya.
Chuck Brew tidak hanya datang kepadaku membawa segepok naskah tebal – beliau datang dengan membawa semangat yang menyala-nyala. Ia tak hanya menulis naskah, tetapi ia juga menjalani laku pengorbanan seperti Resi Bisma Dewabrata, demi melahirkan anak kandung kebudayaannya ini. Latar belakang Chuck Brew sebagai sutradara film, seniman kreatif dan seni rupa, juga pemahat – pendeknya, sebagai seniman – membuatnya tahu betul bagaimana membuat sebuah naskah bukan sekadar bacaan, tetapi juga sebagai sebuah karya seni – dan wujud kitab ini adalah karya seni itu sendiri. Aku melihat seolah-olah Chuck Brew tidak sedang menulis buku, tetapi menciptakan sebuah artefak budaya, lengkap dengan segala detailnya yang teliti dan apik. Untuk itu, beliau menyetir sendiri mobilnya dari Jakarta langsung menuju Solo, demi menemui para seniman wayang, khusus untuk meminta mereka menggambar langsung detail rupa sekitar 400 wayang kulit di kertas kalkir. Beliau juga menyambangi keraton Solo untuk meminta izin memotret langsung koleksi wayang kulit kraton dengan bantuan fotografer profesional. Beliau, dibantu dua orang lainnya, satu dhalang dan satu ahli filsafat wayang, melakukan riset mendalam di pusat-pusat kegiatan wayang seperti Museum Wayang, Senawangi, Persatuan Dhalang, dan sebagainya. Jangan tanyakan berapa biaya yang dengan sukarela beliau keluarkan dari kantong sendiri untuk memperlancar proses ini: beliau adalah salah dari segelintir orang yang mau mengorbankan tenaga, waktu dan uang demi menulis buku! Jika tanpa cinta, mungkinkah itu dilakukan? Dengan cinta, beliau menimang-nimang, mengelus-elus dan merawat seluruh proses penciptaan, seperti ibu yang dengan sabar dan tabah menanti kelahiran buah hatinya.
Ini adalah kitab tentang Wayang, yang adalah refleksi dari “bayangan” sifat-sifat manusia. Kisah wayang adalah kisah tentang manusia dengan seluruh karakternya, dengan seluruh filosofi kehidupan yang begitu rumit, arif dan luas. Ia tak memotret manusia hanya dari kacamata hitam-putih – sebab para empu tahu bahwa manusia lebih sering bergerak di wilayah abu-abu. Tetapi wayang tidak sekadar cerita dan tontonan, tetapi juga pelajaran dan tuntunan, sebab yang dikisahkan adalah soal-soal kemanusiaan dan juga tentang hubungannya dengan Sang Hyang Pangeran Kang Murbeng Dumadi. Wayang adalah bayang-bayang, adalah boneka, dan penggeraknya adalah Dhalang: seperti manusia, kita adalah seperti wayang yang digerakkan Tuhan.. Kita juga adalah wayang dalam arti “bayang-bayang Tuhan,” sebab “manusia diciptakan menurut Citra (Bayangan, Gambaran) Tuhan Yang Maha Rahman” – dan sebagai “Bayangan Tuhan” itulah maka kita diberi hak menjadi “Khalifah di atas bumi-Nya.” Hubungan Dhalang-Kelir (Wayang) adalah perlambang hubungan Tuhan dan Manusia: Manusia adalah tajalli (iluminasi, pancaran) dari cahaya-Nya yang memancar pada kelir (alam semesta). Seperti tersirat dalam sebuah tembang macapat, pupuh Kinanti
Kadi ta upaminipun
Dhalang wayang lawan kelir
Dhalang pan wujud mutlak
Wayange wujud ilapi
Kelire akyan sabitah
Karone nyata ing kelir
Karena begitu dekatnya kisah wayang dengan kehidupan dan diri pribadi kita yang paling dalam, tak mengherankan jika ia menjadi tontonan dan tuntunan yang mampu menghanyutkan siapa saja yang mau menghargai hidup, yang mau memandang hidup sebagai sebuah anugerah Ilahi, dan mau menyadari bahwa pada akhirnya kita, semua manusia, akan kembali kepada-Nya. Meski orang tahu yang mereka tonton hanyalah kisah yang dipentaskan dengan karakter dari kulit dan kayu, tetapi mereka bisa tenggelam dalam kisahnya karena kisah-kisah itu berhubungan langsung dengan inti dari kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang digambarkan oleh seorang empu:
“Tiyang aningali ringgit punika lajeng wonten ingkang nangis, sumlengeran sarta prihatos ing manahipun, sanajan sampun sumerep ingkang tinonton wau wantahipun namung wawucal ingukir tinatah kadapur tiyang saged solah bawa sarta wicanten. Tiyang ingkang ningali ringgit wau upaminpun namung kados dene tiyang ingkang angangsa-angsa dateng kadonyan ingkang sarwa kanikmatan, temahan ing sakala kataliweng ing manah, mboten sumerep manawi punika wauang ingkang dewalipun kados siluman, utawi lugunipun namung kados sulapan mawon. Sejatosipun wayang punika mobah mosik wicanten, gumujeng, suka, wonteng ingkang nangis lan prihatos, ebahipun manut pikajengipun Ki Dhalang ingkang nglampahaken wayang punika wau.”
Orang yang melihat pertunjukan wayang ada yang menangis serta prihatin di hati meski tahu kalau yang dilihat itu hanyalah wujud yang diukir dan ditatah dibentuk seperti manusia, bisa bergerak dan bicara. Mereka yang menyaksikan wayang adalah seperti mansia yang pada awalnya mengagungkan keduniawian, lalu mendadak sadar bahwa semua [kehidupan duniawi] itu hanyalah bayang-bayang saja yang datang dan pergi seperti siluman. Sesungguhnya wayang itu bergerak dan berbicara, tertawa dan menangis, menurut kehendak Ki Dhalang …]
Kisah wayang juga mengajarkan bahwa “lakon” wayang tak ada artinya jika tidak “dilakoni.” Wayang adalah perlambang dari eksistensi manusia yang terus-menerus mencari Kebenaran dan Kesejatian hidup. Kisahnya lahir dari perenungan mendalam para empu yang telah menghayati hidup sepenuhnya, yang telah menerobos batas ruang dan waktu – tak heran jika kisah wayang dan medium penyajiannya terus bertahan hingga berabad-abad dan terpelihara dengan rapi.
Matur Nuwun Mas Heru Sudjarwo ... mugi adikarya puniko dados lantaran tekaning barokah kagem panjenengan .. sepindah malih: Barkallahu laka..amin..
Mbah Kanyut al-Kenthiri al-Jawi, salah satu editor Kakilangit Kencana.








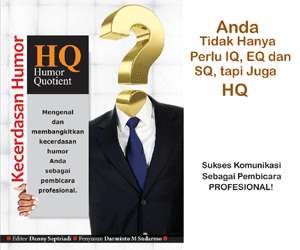






















































0 komentar:
Post a Comment